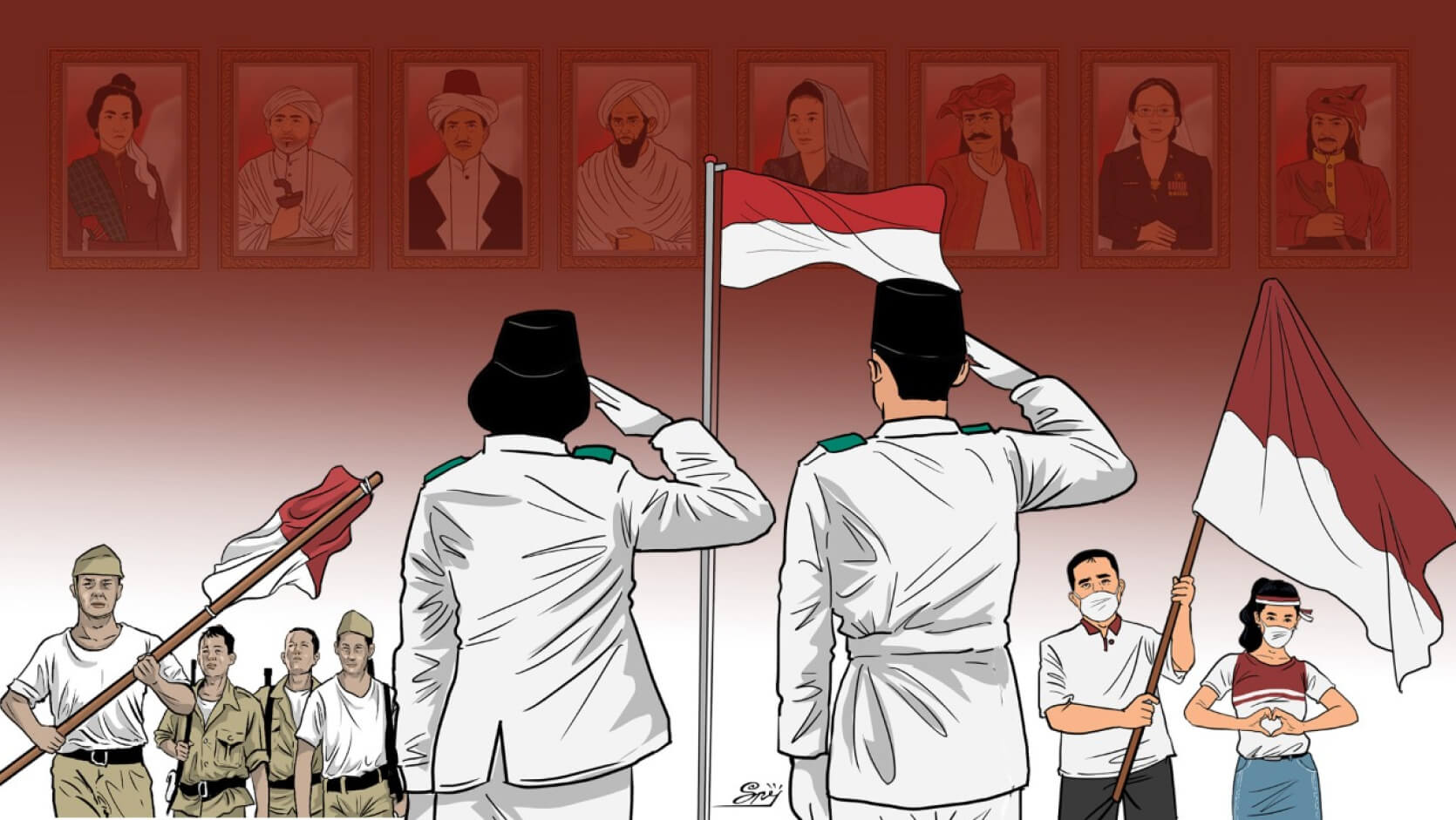Hilangnya Mandat Aspirasi Rakyat pada DPR
Asyraf Alharaer Assegaf
Ketua Komisi Aspirasi Senat Mahasiswa IAIN Parepare
DPR dalam suasana persetujuan kenaikan tunjangannya, kini menjadi potret buram wajah parlemen kita. Nampak berjoget Nafa Urbach, Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya menjadi fenomena yang mencuat ke publik.
Ditengah situasi ekonomi yang mencekek rakyat, aksi itu seperti pesta kecil yang menagaskan jarak antara wakil rakyat dan realitas masyarakat. Alih-alih mencerminkan keseriusan dalam menjalankan amanah. Momen itu justru menunjukkan betapa ringan mereka mamaknai mandat rakyat.
Kursi parlemen seolah hanya panggung hiburan. Seharusnya tiap keputusan tentang gaji, tunjangan, atau fasilitas DPR dibicarakan dengan penuh kepekaan terhadap kondisi bangsa. Namun justru yang terlihat sebaliknya: keceriaan berlebihan dibalik kebijakan kontroversial.
Adegan yang telah dilakukan banyak mengirim pesan simbolik, bahwa kesejahteraan wakil rakyat lebih mendesak daripada jeritan rakyat. Rakyat yang tiap hari bergulat harga kebutuhan pokok, pengangguran, dan pelayanan publik tak kunjung merata.
Ketika wakil rakyat larut dalam euphoria maka rakyat jauh dari luar gedung parlemen hanya bisa menatap dengan getir. Tentu ini menegaskan bahwa DPR semakin kehilangan mandat aspirasi rakyat.
Jika hanya joget dan tawa yang ditunjukkan para wakil rakyat itu, tentu bukan sekadar hiburan sepele, melainkan refleksi dari kultur politik yang makin dangkal. Publik pun merasa tidak sedang diwakili melainkan dipertontonkan sebuah drama yang mengabaikan empati.
Padahal, rakyat menitipkan suara mereka bukan untuk melihat koreografi politik penuh kegembiraan pribadi, tetapi untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Mungkin, lambat laun jika kondisi ini terus berulang, kepercayaan rakyat terhadap DPR kian runtuh. Aksi-aksi kecil yang dianggap “hiburan” justru bisa menjadi bara besar yang memicu ketidakpuasan rakyat.
DPR perlu belajar bahwa simbol, sikap, dan perilaku publik para wakil rakyat adalah wajah dari institusi itu sendiri. Joget dan persetujuan tunjangan di saat rakyat menderita bukan hanya soal etika politik yang tercederai, melainkan juga tanda nyata bahwa mandat rakyat perlahan lenyap dari gedung parlemen.
Kursi Parlemen Bukan Hadiah
Tentu kita tidak lupa bahwa secara konstitusi kursi parlemen bukanlah hadiah. Ia juga bukan hak Istimewa, bukan lahir dari ketenaran, poularitas, atau kekayaan. Kursi ada karena rakyat, jutaan suara yang berjejal dikotak-kotak suara ditiap lima tahun sekali.
Sebagai lembaga representasi DPR pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, keberadaan DPR hanya sah sejauh ia menjadi saluran dari suara rakyat. Begitu ia terputus dari rakyat, maka ia kehilangan alasan moral untuk bertahan.
Namun, faktanya semakin banyak wakil rakyat yang duduk dengan nyaman seolah-olah kursi itu milik pribadi. Mereka lupa bahwa mandat politik bukanlah tiket untuk berkuasa, melainkan amanat untuk mengabdi. Mungkin tambah menyedihkan, kursi itu kini sering diperlakukan layaknya panggung hiburan.
Rakyat sesungguhnya hanya menuntut hal sederhana, agar suaranya tidak diperdagangkan, agar kebutuhannya tidak dikalahkan oleh kepentingan elite. Namun yang kerap terlihat justru sebaliknya, sementara rakyat terus dihantui harga kebutuhan yang melambung.
Kursi parlemen bukan tempat panggung joget, bukan juga singgasana untuk menari di atas penderitaan orang banyak. Mestinya menjadi ruang pertemuan nurani, ruang tempat di mana jerit petani, nelayan, buruh, dan mahasiswa diterjemahkan jadi undang-undang yang adil.
Jika para wakil rakyat lebih sibuk berpesta ketimbang mendengar, maka sejatinya mereka sedang menutup telinga dari mandat yang diberikan rakyat. Sejarah bahkan sudah berkali-kali memberi pelajaran. Dari jalanan yang membara hingga suara-suara kritis yang dipinggirkan, selalu ada harga yang harus dibayar ketika wakil rakyat melupakan rakyat.
Legitimasi politik tidak bisa ditopang selamanya oleh angka hasil pemilu. Itu hanya bisa bertahan selama masih ada kepercayaan. Begitu kepercayaan itu retak, kursi-kursi empuk perwakilan rakyat bisa berubah jadi beban.
Karena itu, perlu diingat lagi bahwa kursi parlemen hanyalah titipan. Ada masa dikembalikan kepada rakyat dan wajib merasa dituntut untuk mempertanggungjawabkan tiap keputusan kepada rakyat, bukan sekadar menikmati fasilitas.
Krisis Representasi
Kenyataan ini telah lahir krisis representasi. Rakyat merasa diabaikan setelah bilik suara ditutup, janji kampanye tinggal slogan yang terlupakan. Suara rakyat hanya dipakai mendongkrak elektabilitas kemudian dilupakan begitu palu sidang diketuk.
Survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada 27 Januari 2025 menunjukkan, tingkat kepercayaan publik terhadap DPR hanya mencapai 69 persen. Angka itu menempatkan DPR di urutan ke-10 dari 11 lembaga yang diukur. Sementara posisi paling besar ditempati partai politik, dengan tingkat kepercayaan publik yang lebih rendah lagi, yakni 62 persen.
Fenomena ini menegaskan bahwa ada jurang yang semakin melebar antara mereka yang duduk di kursi parlemen dengan rakyat yang mereka wakili. Krisis representasi ini juga disuburkan oleh perilaku elite.
Alih-alih membicarakan kebutuhan mendesak rakyat—subsidi pangan, akses pendidikan, hingga perbaikan layanan publik. DPR justru sibuk mengurus kepentingan sendiri. Maka wajar jika rakyat merasa hanya dijadikan korban elektoral, mencari pada saat pemilu, dibuang setelahnya.
Banyak lagi, sebagian wakil rakyat justru menjadikan panggung politik sebagai ruang personal branding, menyikapi tindakan-tindakan mereka tentu lebih mirip konten hiburan ketimbang keputusan yang menyentuh kepentingan rakyat.
Dalam kondisi seperti ini tentu krisis representasi DPR kian terasa nyata. Lembaga yang seharusnya menjadi corong aspirasi rakyat justru makin jauh dari denyut kebutuhan warganya. Alih-alih menghadirkan kebijakan yang menyejukkan, publik kerap disuguhi tontonan yang memicu kekecewawaan.
Rakyat akhirnya memilih turun ke jalan sebagai bahasa terakhir untuk menyuarakan aspirasi yang tak pernah menemukan telinga di gedung parlemen. Namun jalanan bukanlah ruang yang aman. Teriakan protes, langkah massa, selalu berhadapan dengan dinding aparat.
Ketegangan yang membesar menjelma kericuhan, dan dalam situasi kacau itu, yang kerap menjadi korban bukan mereka yang memegang kuasa, melainkan rakyat kecil yang hanya menjalani hidup sehari-hari.
Affan Kurniawan, driver ojek online meregang nyawa di tengah rusuh. Ia bukan aktivis politik, bukan orator di mimbar aksi, apalagi pejabat negara. Ia hanya rakyat biasa yang tengah mencari rezeki, tetapi takdirnya terenggut oleh situasi politik yang gagal dikelola dengan bijak.
Kematian Affan tentu menyisakan luka mendalam dan mencerminkan kehidupan pahit, bahwa drama dalam politik negeri ini, justru yang jadi korban mereka paling lemah. DPR gagal menjalankan mandat representasi, aparat gagal memastikan ruang protes tetap damai, dan negara gagal melindungi warganya.
Hilangnya satu nyawa rakyat kecil bukan sekadar angka dalam laporan, melainkan simbol retaknya kontrak sosial antara rakyat dan negara. Apa artinya demokrasi jika suara rakyat hanya menjadi bahan bakar elektabilitas, sementara darah rakyat tumpah di jalanan?
Tragedi ini seharusnya menjadi alarm keras bagi para pemegang kekuasaan. Representasi yang hancur di gedung parlemen kini berbalik menjadi api di jalanan. Dan setiap kali api itu menyala ada risiko korban baru berjatuhan.
Pertanyaan yang harus dijawab DPR hari ini bukan sekadar soal berapa besar tunjangan yang mereka nikmati, melainkan apakah mereka masih layak disebut wakil rakyat?
Sebab, bila mandat aspirasi terus diabaikan maka rakyat akan mencari jalannya sendiri, meski jalan itu berujung pada kerusuhan dan kehilangan yang tak seharusnya terjadi. Semakin rakyat merasa terasing, semakin besar peluang lahirnya gelombang perlawanan.
Karena itu krisis representasi bukan sekadar persoalan citra DPR, melainkan ancaman terhadap legitimasi sistem politik itu sendiri. Jika wakil rakyat tidak segera menata ulang kompas moral dan keberpihakan, maka kursi parlemen hanya akan menjadi simbol kosong, dan megah dari luar, rapuh di dalam.
Hilangnya mandat aspirasi rakyat pada DPR harus dipandang sebagai peringatan yang serius. Keputusan politik yang diiringi pesta, apalagi dalam situasi rakyat terhimpit, hanya akan memperdalam krisis representasi.
Tentu seharusnya kita mengingat, bahwa ini bukanlah hadiah, ini adalah titipan rakyat. Mandat diberikan sebagai rasa percaya jika tidak, legitimasi politik itu akan runtuh dan demokrasi hanya bertahan jika menempatkan kepentingan publik diatas kepentingan pribadi.
“Demokrasi tidak hanya berarti pemerintahan dari rakyat, tetapi juga untuk rakyat dan oleh rakyat.” Bung Hatta.


 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Serdadu.id
Serdadu.id Beritautama.co
Beritautama.co kalbarsatu.id
kalbarsatu.id surau.co
surau.co